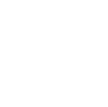Reposisi Ulama Aceh
Dibaca: 3037
Oleh Teuku Zulkhairi
MENCERMATI kiprah ulama Aceh akhir-akhir ini dalam memainkan perannya menjelang digelarnya prosesi pilkada sedikit memiriskan hati kita sebagai masyarakat. Ulama yang sejatinya diharapkan sebagai simbol pemersatu, penasihat dan pengontrol, namun terjebak dalam praktik legitimasi sikap politik satu pihak dan mendelegitimasi sikap politik pihak lainnya. Misalnya seperti munculnya sekelompok ulama yang mendesak penundaan pilkada maupun sekelompok ulama lainnya yang mendukung prosesi pilkada digelar tepat waktu.
Tulisan ini bukan bermaksud untuk menggugat status keulamaan siapa pun. Ulama tetap figur sentral di mata penulis dan tentu saja di mata semua elemen masyarakat Aceh lainnya. Meskipun relasi ulama dan umara bukan sesuatu hal yang baru, tapi dengan melihat dinamika terkini pentas perpolitikan di Aceh dan relevansinya dengan kiprah ideal para ulama di masa silam, mendudukkan kembali posisi (reposisi) ulama Aceh dan tanggung jawab mereka nampaknya adalah sebuah keniscayaan. Ulama seharusnya tidak berperan untuk melegitimasi suatu kepentingan kelompok atau calon tertentu ditengah kondisi perpolitikan Aceh yang sedang bagai `api dalam sekam'.
Sikap ulama yang melegetimasi sikap satu pihak pada akhirnya akan bermakna delegitimasi bagi pihak lainnya. Sikap ini tentu sangat berbahaya bagi eksistensi kiprah ulama sendiri, selain tentu saja bagi keberlangsungan damai di Aceh. Sebab, ulama adalah simbol pemersatu. Hancurnya simbol ini akan mengakhiri persatuan umat.
Sebagai pewaris para Nabi (warasatul anbiya), ulama dianggap sebagai simbol perdamaian dan tempat meminta solusi, sekaligus sebagai penengah dan mediator dalam sebuah konflik, karena karakteristik para Nabiyullah diyakini dimiliki oleh para ulama, seperti sifat Shiddiq (benar/jujur), Tabligh (aspiratif/menyampaikan yang haq), Amanah (bisa dipercaya) dan Fathanah (cerdas). Dengan berbagai kelebihan tersebut, ulama di Aceh diharapkan menjadi pengontrol bagi jalannya prosesi setiap agenda politik dan perubahan. Ulama milik semua elemen masyarakat, bukan suatu kelompok.
Dengan posisinya sebagai mediator perdamaian, ulama harus mampu bersikap netral dalam pentas perpolitikan. Jika tidak, maka masyarakat akan terbelah. Kran konflik menjadi mudah saja terbuka saat masyarakat sudah terkotak- kotak. Ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Abu Nu'man, bahwa Nabi pernah menyatakan: "Dua macam golongan manusia yang apabila keduanya baik maka baiklah masyarakat. Tetapi apabila keduanyaa rusak maka rusaklah masyarakat itu. Karena ulama harus memerankan diri dalam rangka kebaikan masyarakat, termasuk berdiri pada posisi ideal sesuai dengan posisinya sebagai pewaris para Nabi.
Sebab, dalam konteks Aceh, seberapa jauh konteks agama bisa dibawa dalam ranah politik Aceh? Apa relevansinya? Apa alasan kuat dari perspektif agama untuk memberikan legitimasi kepada suatu kelompok dan mendelegitimasi kelompok lainnya? Bukankah semua di sini adalah muslim dan sama-sama punya orientasi untuk perbaikan agama dan masyarakat dengan kekurangannya masing-masing diantara kelompok tersebut? Selain itu, bukankah perdamaian dalam perspektif agama merupakan suatu kewajiban dan dengan ulama diharapkan sebagai mediatornya?
Dalam sejarahnya, tidak jarang kita saksikan bahwa legitimasi ulama kepada satu pihak akan memunculkan resistensi pihak tersebut kepada pihak yang dilegitimasi. Resistensi itu bisa berakibat fatal. Karena legitimasi tadi akan dianggap sebagai pembenaran ulama bagi satu pihak dan `penyalahan' kepada pihak lain. Selain itu, posisi keulamaan seorang ulama pun di balik itu juga akan mendapatkan sikap resistensi sebagian masyarakat lainnya.
Efeknya, kebenaran-kebenaran lain yang akan disampaikan para ulama akan menjadi sulit didengar dan dipatuhi oleh segenap komponen masyarakat. Ini tentu bukan sesuatu yang ideal. Jika ulama sebagai figur sentral dalam menerjemahkan agama dianggap telah membenarkan satu kelompok, maka kemungkinan lahirnya anarkisme satu kelompok yang diberikan legitimasi tersebut terhadap kelompok yang didelegitimasi merupakan sebuah konsekuensi yang sangat terbuka. Oleh sebagian orang, legitimasi ulama kepada mereka bisa saja dijadikan sebagai justifikasi untuk melakukan tindakan anarkisme maupun tekanan psikologis kepada lawannya. Ini tentu bukan kondisi yang ideal serta sangat jauh dari semangat Alquran dan Hadits.
Dalam kontek upaya reposisi kiprah ulama ini, menurut Iskandar Budiman (Tribun, 25 Oktober 2011), ada beberapa hal menarik yang dapat dijadikan format peran dan posisi para ulama Aceh masa kini dalam menata kembali kehidupan umat di tengah-tengah maraknya arus globalisasi. Pertama, sikap kearifan ulama dalam menyikapi berbagai masalah agama tidak terlalu konfrontatif dan selalu diupayakan secara persuasif; kedua, menghargai dan menjunjung tinggi "adab majelis" dengan saling menghargai pendapat orang lain; ketiga, membuka wawasan dengan tidak serta-merta mengenakan hukuman tanpa didukung oleh data-data yang sahih (masih memperhatikan sikap toleransi/tasamuh); keempat, jika terjadi selisih faham kembali kepada Allah dan Rasul (Alquran dan Sunnah); kelima, ulama tidak hidup atas menara gading untuk kepentingan partai/kelompoknya yang mengabaikan substansi syari`at serta kepentingan umat. Artinya, dalam konteks politik, yang seharusnya dilakukan para ulama adalah membangun kesadaran politik umat, yaitu kesadaran umat tentang bagaimana mereka memelihara urusannya dengan syariat Islam.
Tawaran posisi ideal bagi ulama ini selayaknya mendapatkan sambutan dari kalangan ulama demi menjaga kewibawaan dan marwah ulama itu sendiri. Bahwa ulama silahkan saja berpolitik dan menjalin relasi dengan penguasa, tapi ulama harus mampu mendudukan posisi idealnya agar tidak terjebak dalam kepentingan pragmatis satu pihak. Baik pihak yang mendukung penundaan pilkada, maupun yang mendukung pilkada tepat waktu.
Ulama-ulama yang ideal seperti ini pasti akan terus didengar oleh masyarakat dan jauh dari sikap resistensi mereka. Sebaliknya, ulama yang terjerumus dalam kepentingan politik praktis satu pihak dipastikan akan mendapatkan resistensi dari pendukung sikap politik pihak lainnya. Pada situasi seperti ini, berbagai kebenaran dari nilai-nilai agama yang akan disampaikan ulama akan sulit didengar oleh masyarakat. Akibatnya pun sangat fatal, umat akan diliputi oleh awan kebodohan.
Barangkali di sini ulama kita perlu belajar ke Iran terkait posisi strategis yang bisa mereka perankan dalam pentas politik. Di Iran, ulama tidak melibatkan untuk mendukung satu kandidat dalam pemilihan raya. Mereka berperan saat menjaring para kandidat yang mana yang layak dan yang tidak layak. Saat kandidat yang layak telah ditetapkan, maka ulama tidak lagi ikut campur untuk dukung mendukung salah satu kandidat demi menjaga persatuan masyarakat. Maka ulama Aceh seharusnya juga bisa berperan sebagai pengontrol jalannya agenda-agenda politik di Aceh agar semua sikap pelaku politik serta orientasi politiknya bisa selalu dalam jalan kebenaran. Semoga saja!
* Penulis adalah Ketua Senat Mahasiswa Pascasarjana IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh.
MENCERMATI kiprah ulama Aceh akhir-akhir ini dalam memainkan perannya menjelang digelarnya prosesi pilkada sedikit memiriskan hati kita sebagai masyarakat. Ulama yang sejatinya diharapkan sebagai simbol pemersatu, penasihat dan pengontrol, namun terjebak dalam praktik legitimasi sikap politik satu pihak dan mendelegitimasi sikap politik pihak lainnya. Misalnya seperti munculnya sekelompok ulama yang mendesak penundaan pilkada maupun sekelompok ulama lainnya yang mendukung prosesi pilkada digelar tepat waktu.
Tulisan ini bukan bermaksud untuk menggugat status keulamaan siapa pun. Ulama tetap figur sentral di mata penulis dan tentu saja di mata semua elemen masyarakat Aceh lainnya. Meskipun relasi ulama dan umara bukan sesuatu hal yang baru, tapi dengan melihat dinamika terkini pentas perpolitikan di Aceh dan relevansinya dengan kiprah ideal para ulama di masa silam, mendudukkan kembali posisi (reposisi) ulama Aceh dan tanggung jawab mereka nampaknya adalah sebuah keniscayaan. Ulama seharusnya tidak berperan untuk melegitimasi suatu kepentingan kelompok atau calon tertentu ditengah kondisi perpolitikan Aceh yang sedang bagai `api dalam sekam'.
Sikap ulama yang melegetimasi sikap satu pihak pada akhirnya akan bermakna delegitimasi bagi pihak lainnya. Sikap ini tentu sangat berbahaya bagi eksistensi kiprah ulama sendiri, selain tentu saja bagi keberlangsungan damai di Aceh. Sebab, ulama adalah simbol pemersatu. Hancurnya simbol ini akan mengakhiri persatuan umat.
Sebagai pewaris para Nabi (warasatul anbiya), ulama dianggap sebagai simbol perdamaian dan tempat meminta solusi, sekaligus sebagai penengah dan mediator dalam sebuah konflik, karena karakteristik para Nabiyullah diyakini dimiliki oleh para ulama, seperti sifat Shiddiq (benar/jujur), Tabligh (aspiratif/menyampaikan yang haq), Amanah (bisa dipercaya) dan Fathanah (cerdas). Dengan berbagai kelebihan tersebut, ulama di Aceh diharapkan menjadi pengontrol bagi jalannya prosesi setiap agenda politik dan perubahan. Ulama milik semua elemen masyarakat, bukan suatu kelompok.
Dengan posisinya sebagai mediator perdamaian, ulama harus mampu bersikap netral dalam pentas perpolitikan. Jika tidak, maka masyarakat akan terbelah. Kran konflik menjadi mudah saja terbuka saat masyarakat sudah terkotak- kotak. Ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Abu Nu'man, bahwa Nabi pernah menyatakan: "Dua macam golongan manusia yang apabila keduanya baik maka baiklah masyarakat. Tetapi apabila keduanyaa rusak maka rusaklah masyarakat itu. Karena ulama harus memerankan diri dalam rangka kebaikan masyarakat, termasuk berdiri pada posisi ideal sesuai dengan posisinya sebagai pewaris para Nabi.
Sebab, dalam konteks Aceh, seberapa jauh konteks agama bisa dibawa dalam ranah politik Aceh? Apa relevansinya? Apa alasan kuat dari perspektif agama untuk memberikan legitimasi kepada suatu kelompok dan mendelegitimasi kelompok lainnya? Bukankah semua di sini adalah muslim dan sama-sama punya orientasi untuk perbaikan agama dan masyarakat dengan kekurangannya masing-masing diantara kelompok tersebut? Selain itu, bukankah perdamaian dalam perspektif agama merupakan suatu kewajiban dan dengan ulama diharapkan sebagai mediatornya?
Dalam sejarahnya, tidak jarang kita saksikan bahwa legitimasi ulama kepada satu pihak akan memunculkan resistensi pihak tersebut kepada pihak yang dilegitimasi. Resistensi itu bisa berakibat fatal. Karena legitimasi tadi akan dianggap sebagai pembenaran ulama bagi satu pihak dan `penyalahan' kepada pihak lain. Selain itu, posisi keulamaan seorang ulama pun di balik itu juga akan mendapatkan sikap resistensi sebagian masyarakat lainnya.
Efeknya, kebenaran-kebenaran lain yang akan disampaikan para ulama akan menjadi sulit didengar dan dipatuhi oleh segenap komponen masyarakat. Ini tentu bukan sesuatu yang ideal. Jika ulama sebagai figur sentral dalam menerjemahkan agama dianggap telah membenarkan satu kelompok, maka kemungkinan lahirnya anarkisme satu kelompok yang diberikan legitimasi tersebut terhadap kelompok yang didelegitimasi merupakan sebuah konsekuensi yang sangat terbuka. Oleh sebagian orang, legitimasi ulama kepada mereka bisa saja dijadikan sebagai justifikasi untuk melakukan tindakan anarkisme maupun tekanan psikologis kepada lawannya. Ini tentu bukan kondisi yang ideal serta sangat jauh dari semangat Alquran dan Hadits.
Dalam kontek upaya reposisi kiprah ulama ini, menurut Iskandar Budiman (Tribun, 25 Oktober 2011), ada beberapa hal menarik yang dapat dijadikan format peran dan posisi para ulama Aceh masa kini dalam menata kembali kehidupan umat di tengah-tengah maraknya arus globalisasi. Pertama, sikap kearifan ulama dalam menyikapi berbagai masalah agama tidak terlalu konfrontatif dan selalu diupayakan secara persuasif; kedua, menghargai dan menjunjung tinggi "adab majelis" dengan saling menghargai pendapat orang lain; ketiga, membuka wawasan dengan tidak serta-merta mengenakan hukuman tanpa didukung oleh data-data yang sahih (masih memperhatikan sikap toleransi/tasamuh); keempat, jika terjadi selisih faham kembali kepada Allah dan Rasul (Alquran dan Sunnah); kelima, ulama tidak hidup atas menara gading untuk kepentingan partai/kelompoknya yang mengabaikan substansi syari`at serta kepentingan umat. Artinya, dalam konteks politik, yang seharusnya dilakukan para ulama adalah membangun kesadaran politik umat, yaitu kesadaran umat tentang bagaimana mereka memelihara urusannya dengan syariat Islam.
Tawaran posisi ideal bagi ulama ini selayaknya mendapatkan sambutan dari kalangan ulama demi menjaga kewibawaan dan marwah ulama itu sendiri. Bahwa ulama silahkan saja berpolitik dan menjalin relasi dengan penguasa, tapi ulama harus mampu mendudukan posisi idealnya agar tidak terjebak dalam kepentingan pragmatis satu pihak. Baik pihak yang mendukung penundaan pilkada, maupun yang mendukung pilkada tepat waktu.
Ulama-ulama yang ideal seperti ini pasti akan terus didengar oleh masyarakat dan jauh dari sikap resistensi mereka. Sebaliknya, ulama yang terjerumus dalam kepentingan politik praktis satu pihak dipastikan akan mendapatkan resistensi dari pendukung sikap politik pihak lainnya. Pada situasi seperti ini, berbagai kebenaran dari nilai-nilai agama yang akan disampaikan ulama akan sulit didengar oleh masyarakat. Akibatnya pun sangat fatal, umat akan diliputi oleh awan kebodohan.
Barangkali di sini ulama kita perlu belajar ke Iran terkait posisi strategis yang bisa mereka perankan dalam pentas politik. Di Iran, ulama tidak melibatkan untuk mendukung satu kandidat dalam pemilihan raya. Mereka berperan saat menjaring para kandidat yang mana yang layak dan yang tidak layak. Saat kandidat yang layak telah ditetapkan, maka ulama tidak lagi ikut campur untuk dukung mendukung salah satu kandidat demi menjaga persatuan masyarakat. Maka ulama Aceh seharusnya juga bisa berperan sebagai pengontrol jalannya agenda-agenda politik di Aceh agar semua sikap pelaku politik serta orientasi politiknya bisa selalu dalam jalan kebenaran. Semoga saja!
* Penulis adalah Ketua Senat Mahasiswa Pascasarjana IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh.
Tags:
Arsip Berita